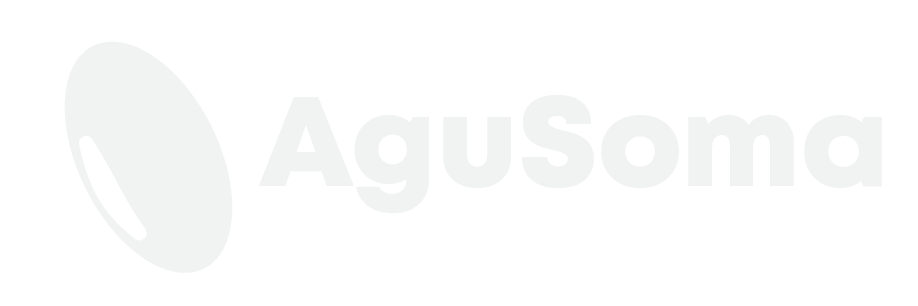Baru-baru ini, Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Nama Indonesia muncul dalam sebuah studi internasional bernama Global Flourishing Study (GFS), yang dipimpin oleh Harvard University bersama Baylor University, Gallup, dan Center for Open Science.
Studi ini melibatkan lebih dari 200.000 responden dari 22 negara, mewakili sekitar 64% populasi dunia. Ada tujuh dimensi kehidupan yang diukur: kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, karakter pro-sosial, hubungan sosial, kesejahteraan spiritual, dan keamanan finansial.
Hasil gelombang pertama dirilis pada 30 April 2025. Mengejutkan, Indonesia menempati posisi pertama dengan skor rata-rata 8,3. Amerika Serikat hanya di peringkat ke-12. Inggris bahkan di posisi ke-20. Para peneliti menekankan bahwa negara maju memang unggul dalam hal finansial, tetapi justru lebih lemah dalam dimensi relasi, makna, karakter, dan spiritualitas.
Sekilas, kabar ini membanggakan. Di tengah segala keterbatasan, ternyata kita memiliki kekuatan pada hal-hal yang tak bisa diukur dengan GDP: gotong royong, ikatan keluarga, rasa syukur, dan iman. Modal sosial ini kerap diremehkan, padahal justru inilah kekayaan bangsa.
Namun, apakah kita boleh berpuas diri? Jawabannya: tidak. Studi ini bukan berarti semua aspek kehidupan kita lebih baik daripada negara lain. Ia hanya menyoroti satu sisi kehidupan bangsa. Realitasnya, kita masih tertinggal dalam kemandirian ekonomi, teknologi, pendidikan, bahkan kedaulatan pangan. Jika kita larut dalam euforia, “nomor satu” bisa menjadi candu yang meninabobokan.
Sebaliknya, peringkat ini seharusnya menjadi cermin: mengapa kita unggul dalam relasi sosial dan spiritual, tetapi tetap terikat dalam ketergantungan impor gandum, kedelai, energi, bahkan teknologi? Di sinilah letak masalahnya: bangsa ini kaya dalam hati, tapi sering miskin kemandirian, prestasi, dan terutama percaya diri.
Kita terlalu polos. Seperti melupakan nasihat leluhur Sunda untuk selalu “Molah mo yatna yatna” jangan sampai tidak waspada. Kita juga terlalu sering “percaya saja tanpa memeriksa”. Terlalu mudah percaya pada kontrak tambang, tanpa meneliti siapa yang paling diuntungkan. Terlalu percaya pada investasi asing, tanpa melihat jebakan ketergantungan. Akibatnya, janji-janji itu justru berubah menjadi pengkhianatan.
Indonesia nomor satu dalam flourishing adalah kabar baik. Tetapi kabar baik ini harus diolah menjadi energi untuk berbenah. Kita harus mampu bercermin: menjaga nilai sosial dan spiritual, sambil memperkuat ekonomi, politik, dan pendidikan.
Flourishing sendiri dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang atau sebuah bangsa bukan hanya mampu bertahan, tetapi bertumbuh secara utuh. Konsep ini lahir dari psikologi positif dan banyak dipakai dalam riset global. Ukurannya tidak hanya ekonomi, melainkan juga kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, kekuatan hubungan sosial, perilaku saling menolong, kesejahteraan spiritual, hingga rasa aman finansial.
Dengan kata lain, flourishing mencerminkan keseimbangan antara jasmani, mental, sosial, dan spiritual. Jika sebuah bangsa dinilai tinggi dalam flourishing, artinya masyarakatnya relatif merasa sehat, bahagia, punya tujuan, saling mendukung, serta memiliki harapan untuk masa depan.
Namun kebanggaan sejati bukan sekadar peringkat di sebuah survei. Kebanggaan itu baru lahir ketika rakyat Indonesia benar-benar hidup merdeka di tanah sendiri: makan dari pangan lokal yang ditanam petaninya, bekerja dengan harga diri, dan berpolitik tanpa dikuasai oligarki.
Itulah makna flourishing yang sesungguhnya. Bangsa yang utuh, kuat lahir dan batin.
Kini saatnya kita berani menilai dengan jujur: apakah sistem ekonomi kapitalis dan pasar bebas sepenuhnya sesuai dengan karakter bangsa kita? Kita adalah bangsa yang unggul dalam relasi sosial, spiritualitas, dan rasa syukur. Tapi sulit bersaing dalam kerakusan, spekulasi, dan metode “segala cara” yang menjadi napas kapitalisme global. Jika kita terus memaksakan diri bermain di panggung mereka, kita hanya akan jadi korban, bukan pemenang.
Karena itu, kita harus kembali pada nasihat leluhur: “Jangan sampai tidak waspada.” Percaya boleh, tapi harus memeriksa. Terbuka pada dunia luar boleh, tapi semua kerja sama harus diverifikasi dan diukur dengan kepentingan rakyat banyak. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa benar-benar berdaulat, menjaga nilai-nilainya, dan menemukan jalan kemandiriannya sendiri.
Referensi
- Harvard T.H. Chan School of Public Health (2025, April 30). Measuring a life well lived: Global Flourishing Study releases first results.
- Harvard Gazette (2025, April 30). More proof that money isn’t everything.
- Global Flourishing Study – Institute for the Quantitative Study of Inclusion, Baylor University.