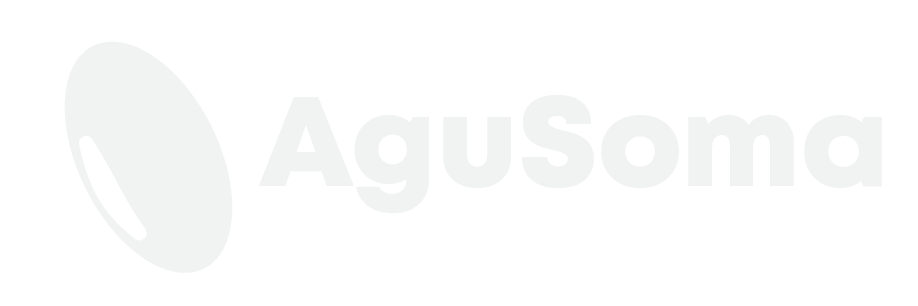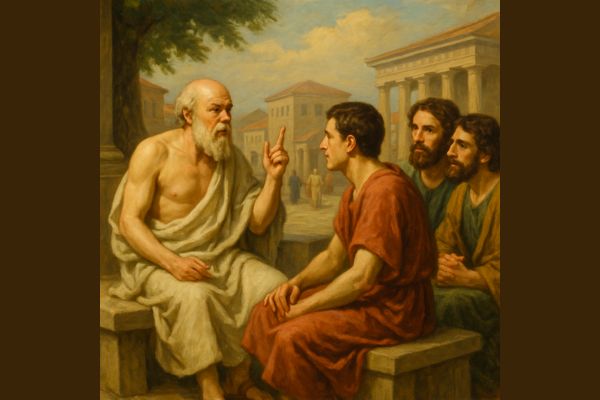
Di Athena abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria sederhana mondar-mandir di pasar dengan kaki telanjang. Ia bukan bangsawan. Bukan juga orang kaya. Namanya Socrates. Socrates tidak mewariskan buku. Tidak juga mendirikan sekolah. Tetapi ia meninggalkan warisan yang menggetarkan dunia hingga kini: keberanian untuk bertanya (Guthrie, 1971).
Socrates percaya, hidup yang tidak diuji bukanlah kehidupan yang layak dijalani. Kalimat ini lahir di pengadilan, saat ia dituduh merusak pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa kota (Plato, Apology). Ia bisa saja memohon belas kasihan agar selamat dari hukuman mati. Tetapi ia memilih bertahan pada kebenarannya. Racun mematikan tubuhnya, tetapi namanya abadi sebagai martir kebenaran.
Beberapa pokok ajaran Socrates yang membuatnya dikenang sebagai bapak filsafat:
Pertama, “Kenalilah dirimu sendiri.” Socrates menemukan banyak orang merasa tahu, padahal sebenarnya tidak. Ia justru berani berkata: “Saya tahu bahwa saya tidak tahu” (Plato, Apology). Dari sini lahir kesadaran bahwa kerendahan hati adalah awal kebijaksanaan.
Kedua, “Keutamaan moral sebagai inti kebahagiaan.” Harta dan kekuasaan bukan ukuran hidup yang baik. Yang membuat hidup mulia adalah keadilan, kejujuran, dan kebajikan (Guthrie, 1971). Bagi Socrates, orang yang jahat hanyalah orang yang tidak tahu jalan kebaikan.
Ketiga, “Metode bertanya.” Socrates tidak mengajar dengan ceramah, melainkan dengan pertanyaan. Pertanyaan sederhana tetapi tajam, memaksa orang berpikir ulang. Sampai hari ini, Socratic Method menjadi dasar dalam pendidikan, hukum, dan bahkan ilmu pengetahuan (Brickhouse & Smith, 2004).
Keempat, “Hidup yang diuji.” Socrates menolak hidup yang berjalan begitu saja tanpa refleksi. Ia percaya manusia harus berani menguji keyakinannya, keputusan-keputusannya, bahkan niatnya sendiri. Hidup tanpa ujian hanyalah hidup yang kosong.
Socrates tidak menulis. Tetapi muridnya, Plato, menyalin percakapan-percakapan itu. Lalu Aristoteles, murid Plato, mengembangkan sistem filsafat yang lebih rasional. Karya Aristoteles inilah yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, dibaca dan dikaji oleh para filsuf Muslim (Fakhry, 2002).
Di Andalusia, seorang ulama besar bernama Ibnu Rusyd (Averroes) menjadi penafsir utama pemikiran filsafat Yunani. Ia dijuluki The Commentator. Melalui Ibnu Rusyd, semangat Socrates ikut mengalir dalam tradisi Islam.
Ibnu Rusyd melihat jejak Socrates dalam filsafat: keberanian bertanya, kesadaran akan keterbatasan diri, dan keyakinan bahwa ilmu dan kebajikan tidak bisa dipisahkan (Fakhry, 2002). Semua itu sejalan dengan ajaran Islam tentang hikmah (kebijaksanaan), ‘adl (keadilan), dan muhasabah (refleksi diri).
Ibnu Rusyd membela filsafat bukan untuk melawan agama. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa akal dan wahyu saling melengkapi. Rasionalitas bukan ancaman. Rasionalitas adalah jembatan menuju pemahaman iman yang lebih dalam.
Hari ini kita hidup di tengah banjir informasi. Berita berseliweran, opini bertebaran. Setiap orang merasa paling benar. Padahal, kebenaran sering kali hanyalah kepentingan yang dibungkus kata-kata indah.
Di sinilah kita perlu belajar dari Socrates: berani bertanya “Mengapa?” (Plato, Apology). Jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan penguasa, tokoh, atau bahkan media besar. Menguji bukan berarti tidak percaya. Itu bukti bahwa kita peduli pada kebenaran.
Kita juga butuh keberanian moral seperti Socrates: menolak kompromi ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Dan kita perlu menghidupkan keberanian intelektual seperti Ibnu Rusyd yang yakin bahwa akal dan iman bisa berjalan seiring (Watt, 1996).
Indonesia hari ini membutuhkan keduanya. Berani menguji kebijakan yang lahir dari ruang rapat politik. Berani menguji pola konsumsi yang membuat kita tergantung impor. Berani menguji cara kita memperlakukan bumi yang terus rusak. Tanpa keberanian itu, kita hanya menjadi penonton dalam drama bangsa sendiri.
Socrates mati karena prinsip. Ibnu Rusyd diasingkan karena membela akal. Keduanya membuktikan kebenaran tak bisa dibungkam. Hidup yang diuji adalah hidup yang penuh makna, jujur pada diri sendiri dan setia pada nurani.
Indonesia butuh keberanian itu: menguji kebijakan, pola konsumsi, dan perlakuan kita terhadap bumi. Seperti Socrates dan Ibnu Rusyd, bangsa ini hanya akan maju jika berani bertanya, berani jujur, dan berani setia pada nurani.
Daftar Pustaka
Brickhouse, T. C., & Smith, N. D. (2004). The Philosophy of Socrates. Boulder: Westview Press.
Fakhry, M. (2002). A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia University Press.
Guthrie, W. K. C. (1971). Socrates. Cambridge: Cambridge University Press.
Plato. Apology. Dalam The Dialogues of Plato.
Apology (Plato) – Wikipedia
Watt, W. M. (1996). Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh: Edinburgh University Press.