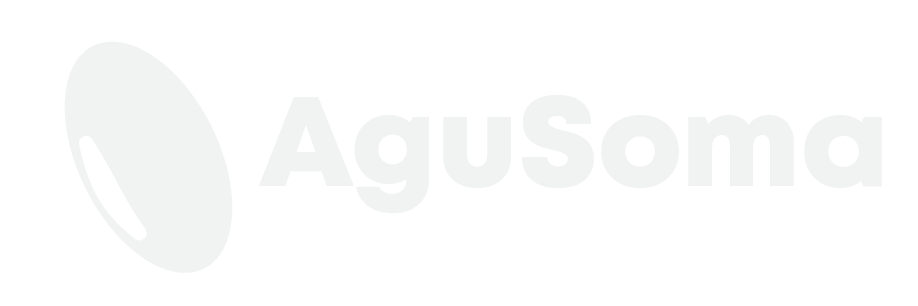Budaya tak pernah netral. Ia bisa menjadi kompas, tapi bisa juga menjadi jeruji tak kasat mata. Tanpa kesadaran budaya, bangsa ini hanya akan mengulang tradisi tanpa sempat mempertanyakan. Kita pun mudah menyerahkan masa depan kepada segelintir elite yang kian serakah. Sementara rakyat cenderung tetap membisu.
Riset Geert Hofstede (1980), psikolog sosial asal Belanda, menunjukkan bagaimana nilai budaya membentuk perilaku masyarakat melalui enam dimensi Utama, yakni: jarak kekuasaan, individualisme, maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang, dan pengendalian diri.
Dalam model penelitiannya, Hofstede memberi skor kepada setiap dimensi antara 0 hingga 100. Skor rendah menunjukkan kecenderungan ke satu sisi, misalnya individualistik atau egaliter. Sementara skor tinggi menandakan kecenderungan kuat ke sisi sebaliknya. Rentang ini bukan ukuran baik atau buruk. Tetapi cerminan nilai dan perilaku sosial suatu masyarakat.
Lewat cermin ini, kita bisa memahami kekuatan dan jebakan budaya kita.
Dimensi Pertama, Jarak Kekuasaan atau Power Distance. Nilainya 78.
Dimensi “jarak kekuasaan” menggambarkan sejauh mana masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar. Skor 78 menandakan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan hierarkis tinggi.
Hubungan antara atasan dan bawahan, guru dan murid, hingga orang tua dan anak cenderung vertikal. Masyarakat terbiasa menghormati otoritas. Bahkan ketika otoritas itu tidak adil. Dalam politik, hal ini memperkuat patronase dan melemahkan partisipasi rakyat.
Jalan keluarnya adalah membangun budaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin sejati bukan yang ditakuti. Peminpin sejati mampu menumbuhkan kepercayaan dan membuka ruang dialog.
Dimensi kedua, Individualisme vs Kolektivisme. Skornya Skor: 14
Dimensi ini menunjukkan seberapa besar individu merasa dirinya bagian dari kelompok. Skor 14 menandakan bahwa masyarakat Indonesia sangat kolektif. Kebersamaan dijunjung tinggi di atas kepentingan pribadi. Namun hal ini juga bisa menekan keberanian untuk berbeda pendapat.
Sebenarnya, kekuatan kita ada pada semangat gotong royong. Nilai yang oleh Koentjaraningrat (1984) disebut inti budaya Indonesia. Namun dalam sistem yang didominasi oligarki seperti sekarang ini, atas nama “persatuan” kerap dijadikan alasan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat.
Jalan keluarnya, kolektivisme perlu diarahkan menjadi solidaritas kritis. Rukun tapi berani mengingatkan. Contoh kecilnya tampak pada koperasi warga, atau komunitas literasi yang tumbuh mandiri tanpa menunggu program dari atas.
Dimensi ketiga adalah “ Penghindaran Ketidakpastian, atau Uncertainty Avoidance. Nilainya 48.
Dimensi ini menggambarkan seberapa nyaman masyarakat menghadapi ketidakpastian. Skor 48 menunjukkan posisi moderat. Masyarakat kita tidak takut berubah. Tapi juga enggan melangkah jauh tanpa kepastian. Akibatnya, banyak hal dibiarkan “mengalir saja” tanpa arah yang jelas.
Bagaimana Jalan keluarnya, Inisiatif lokal harus didorong. Gerakan desa mandiri pangan lokal, misalnya, dan mendorong inovasi komunitas adalah bentuk kemandirian yang membebaskan rakyat dari ketergantungan.
Dimensi keempat, Maskulinitas vs Feminitas. Skornya: 46.
Dimensi ini menilai keseimbangan antara orientasi kompetisi (maskulinitas) dan kepedulian (feminitas). Skor 46 menunjukkan masyarakat Indonesia relatif seimbang. Tapi ruang publik masih sering dikuasai nilai maskulin seperti ambisi dan dominasi.
Jalan keluarnya adalah memperkuat nilai kepemimpinan welas asih. Seperti diajarkan Ki Hadjar Dewantara (1962): “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Pemimpin harus selalu memberi teladan dan memberdayakan, bukan menakut-nakuti rakyat.
Dimensi kelima adalah “Orientasi Jangka Panjang” atau Long-Term Orientation: Nilainya 62.
Dimensi ini mengukur sejauh mana masyarakat menilai masa depan lebih penting daripada masa kini. Skor 62 menandakan orientasi jangka panjang cukup kuat. Tetapi budaya ini sering dimanfaatkan oleh elit untuk menunda keadilan hari ini. Proyek besar atas nama pembangunan tidak selalu menyentuh petani, nelayan, dan UMKM untuk hari ini dengan alasan kebijakan untk orientasi kedepan.
Jalan keluarnya, Visi jangka panjang harus berpihak pada rakyat, bukan kepada elite. Masa depan bangsa tumbuh dari desa, bukan hanya dari ruang rapat para elit.
Dimensi keenam, Indulgence vs Restraint. Skor: 38.
Dimensi ini menunjukkan sejauh mana masyarakat mengekspresikan keinginan dan kebahagiaan. Skor 38 berarti masyarakat Indonesia cenderung menahan diri demi menjaga harmoni sosial. Namun mereka sering mengorbankan kebebasan berekspresi.
Jalan keluarnya, kita harus membangun budaya ekspresi yang sehat dan bermartabat. Anak muda harus dibiasakan berbicara, menulis, dan berkesenian. Seperti diingatkan Soedjatmoko (1983), “pembangunan bangsa harus berakar pada kebudayaan yang membebaskan manusia dari ketakutan dan kebodohan.”
Penutup
Budaya bukan takdir. Budaya harus bisa disadari dan diarahkan. Jangan biarkan budaya menjadi topeng kekuasaan yang menindas. Jadikan budaya sebagai akar keberanian berpikir dan bertindak jujur.
Bangsa yang berani bercermin pada budayanya adalah bangsa yang siap menulis sejarahnya sendiri.
Mari kita mulai mengenal diri, mulai dari memahami budaya, untuk melangkah masa depan.
*Bahan diperoleh dari berbagai sumber. Penulisan dibantu AI