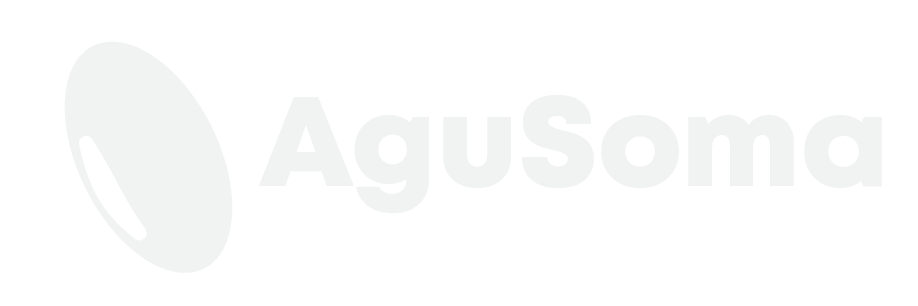Lebih dari dua ribu lima ratus tahun lalu, di negeri Lu, wilayah yang kini dikenal sebagai provinsi Shandong, Tiongkok, lahirlah seorang anak bernama Kong Qiu. Kelak dunia mengenalnya sebagai Konfusius. Ia lahir dari keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ibunya, seorang wanita sederhana, membesarkannya dengan tekun dan penuh nilai moral.
Sejak kecil Konfusius dikenal haus akan pengetahuan. Ia tidak punya guru besar, tapi belajar dari siapa pun: dari para tetua, dari alam, dari kehidupan rakyat jelata. Ketika teman sebayanya bermain, ia belajar tentang tata upacara, sejarah, dan musik kuno. Ia percaya bahwa keindahan dan moral tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang mampu mendengarkan harmoni musik sejati akan memahami harmoni dalam kehidupan.
Di masa mudanya, Konfusius bekerja sebagai pejabat kecil di pemerintahan. Ia memulai dari bawah: mengurus gudang, mencatat hasil panen, dan menata administrasi. Tapi yang ia pikirkan bukan kekuasaan, melainkan bagaimana menata masyarakat dengan moral dan keadilan.
Ia berkelana dari negeri ke negeri. Ia menawarkan gagasan bahwa negara harus dipimpin oleh kebajikan, bukan kekerasan. Tapi para penguasa waktu itu menertawakannya. Ada yang mengusir, ada yang menolak. Bahkan ada yang mencoba membunuhnya. Namun Konfusius tidak membalas kebencian dengan dendam. Ia berkata: “Balas dendam dengan kebajikan, karena itulah cara mengubah hati manusia”.
Setelah bertahun-tahun mengembara tanpa diterima, ia kembali ke negeri Lu. Di sana ia mengajar, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana menjadi manusia sejati. Murid-muridnya datang dari berbagai kalangan: bangsawan, petani, bahkan orang biasa. Ia tidak memandang status, sebab baginya, yang penting bukan dari mana seseorang berasal, tapi apakah ia mau memperbaiki dirinya.
Ketika wafat di usia 72 tahun, Konfusius meninggalkan pesan sederhana kepada muridnya: “Aku bukan yang menciptakan kebenaran, aku hanya mewariskannya.” Ia tidak mendirikan agama, tapi meninggalkan jalan hidup, Dao. Jalan kebajikan yang menuntun manusia pada keharmonisan.
Ajaran Konfusius berakar pada tiga hal: cinta kasih (ren), kesopanan (li), dan keteladanan (de). Nilai-nilai itu sesungguhnya juga tumbuh di tanah air kita. Dalam ajaran Jawa, dikenal ngajeni, menghormati orang lain dengan budi pekerti. Dalam ajaran Sunda, silih asih, silih asah, silih asuh. Di Minang, ada pepatah “budi baek indak ka hilang di nan lamo.” Di Bali, Tri Hita Karana menuntun keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.
Jika di Tiongkok kebajikan disebut ren, maka di Nusantara ia disebut rasa. Jika di sana disebut li, tata moral, maka di sini ia hidup sebagai tatakrama. Kebenaran sejati memang tidak pernah bertentangan. Ia hanya memakai bahasa yang berbeda di setiap tanah.
Namun kini, ajaran-ajaran seperti ini mulai terpinggirkan. Sekolah lebih banyak mengajarkan cara berpikir cepat, bukan cara berpikir bijak. Kita hafal rumus dan teknologi, tapi lupa sopan santun. Kita tahu cara membangun gedung tinggi, tapi tidak tahu cara menundukkan hati. Konfusius pernah berkata: “Negara akan runtuh bila rakyat kehilangan rasa malu.” Dan tidakkah hari ini kita mulai melihat tanda-tanda itu?
Seperti halnya Konfusius yang menolak jabatan demi mempertahankan integritas, kita pun harus berani menolak jalan pintas demi kehormatan. Pemimpin harus menjadi teladan, bukan tontonan. Rakyat harus belajar berbuat baik bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar akan kebaikan itu sendiri.
Saatnya kita memadukan kembali kearifan Timur dan kearifan Nusantara: kebajikan, rasa hormat, dan harmoni sebagai fondasi kemajuan. Bangsa yang kehilangan moralnya sejatinya mundur dalam kemanusiaan. Kemajuan tanpa budi hanyalah ilusi: cepat berlari, tapi menuju kehampaan.
Daftar Pustaka
• Confucius. (1997). The Analects (A. Waley, Trans.). Vintage Classics.
• Fingarette, H. (1972). Confucius: The Secular as Sacred. Harper & Row.
• Mulder, N. (1999). Pribadi dan Masyarakat di Asia Tenggara: Pandangan tentang Manusia dan Masyarakat dalam Kebudayaan Jawa. Kanisius.
• Sutawan, N. (2000). Tri Hita Karana: Konsep dan Implementasi dalam Pembangunan Bali Berkelanjutan. Denpasar: Udayana University Press.
• Tu, W. M. (1985). Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation. State University of New York Press.
• Yao, X. (2000). An Introduction to Confucianism. Cambridge University Press.
*Bahan diperoleh dari berbagai sumber. Penulisan dibantu AI