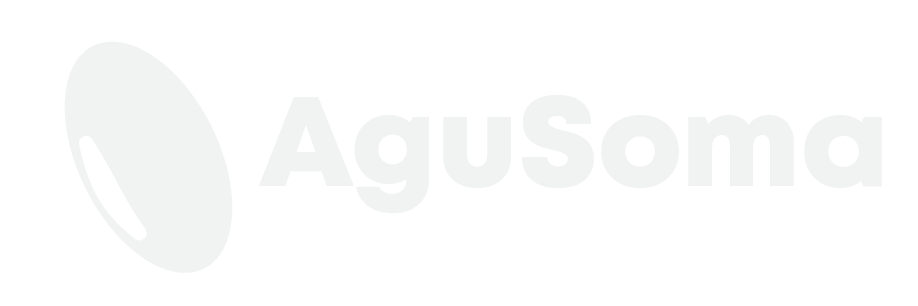Entah karena saking bingungnya, atau karena terlalu percaya diri, pemerintah melalui Kementerian Pertanian kini sedang mencoba hal yang sulit: menanam gandum. Di dataran tinggi Kerinci, Jambi, pemerintah menjadikan 200 hektar lahan sebagai lokasi percobaan gandum perdana (ANTARA News, 24 Juli 2025).
Uji coba ini dipimpin oleh Kementerian Pertanian bersama PTPN IV, dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor gandum yang mencapai 12 juta ton per tahun (Bisnis.com, 26 Juli 2025).
Namun hasil riset sejauh ini tidak menggembirakan. Produktivitas gandum di Indonesia hanya 1,5–2 ton per hektar. Sementara di Australia bisa mencapai 4–6 ton per hektar. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, dibutuhkan sekitar 6 juta hektar lahan gandum.
Sesuatu yang mustahil tanpa mengorbankan lahan pangan lain (ANTARA News, 24 Juli 2025; Jambi BRMP, 6 Agustus 2025).
Masalahnya, bukan hanya soal gandum. Kebijakan ketahanan pangan kita juga terlalu terpaku pada beras. Beras dijadikan simbol kedaulatan pangan. Padahal lahan sawah makin menyusut. Iklim makin sulit diprediksi. Dan konsumsi beras kita sudah terlalu membebani.
Meskipun pemeringtah men-declare bahwa kita sudah swasembada, menggantungkan diri hanya pada beras sama tidak rasionalnya dengan memaksakan swasembada gandum.
Lalu mengapa kita tidak belajar dari kearifan lokal?
Leluhur Nusantara mengandalkan sorgum, singkong, talas, jagung, dan sagu. Semua tumbuh subur di tanah tropis. Semua pernah menjadi energi bangsa. Tetapi hari ini, kita justru menyingkirkan pangan itu.
Kita memilih bergantung pada gandum impor dan beras yang kian terbatas. Mengapa kita harus memaksakan diri mengikuti pola makan berbasis gandum dan nasi?
Ubi, talas, singkong, dan sorgum sesungguhnya memiliki keunggulan yang lebih sesuai bagi bangsa tropis. Indeks glikemik ubi jalar rebus hanya sekitar 44 (University of Sydney, GI Database, 2024). Talas sekitar 53 (FoodData Central, USDA, 2023). Dan sorgum berada di kisaran sedang, 60–66 (International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2016).
Semuanya lebih baik dibanding nasi putih (70–73) atau roti gandum putih yang juga tinggi GI (Mayo Clinic, 2023).
Artinya, pangan lokal kita lebih aman untuk menjaga kestabilan gula darah dan mencegah ledakan penyakit diabetes yang kini membebani negeri. Ubi jalar bahkan kaya beta-karoten (FAO, 2020). Sementara sorgum mengandung serat, protein, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan jantung (FAO, 2020; Nutrients Journal, 2018).
Selain keunggulan gizi, pangan lokal juga lebih ramah ekologi. Singkong tahan kekeringan dan toleran pada tanah miskin hara (FAO, 2020; CIAT, Cassava in the Third Millennium). Sorgum dikenal sebagai tanaman yang paling tahan kekeringan di antara serealia sehingga cocok ditanam di lahan tadah hujan (ICRISAT, 2019; FAO, 2018).
Talas dan ubi jalar tumbuh subur di berbagai kondisi tropis tanpa banyak pupuk kimia. Talas dan ubi telah lama dibudidayakan sebagai pangan rakyat di lahan marginal (FAO, 2020; CIP – International Potato Center, 2017).
Bandingkan dengan padi yang boros air: dibutuhkan sekitar 2.500 liter air untuk menghasilkan 1 kg beras (IRRI, 2015). Sementara gandum jelas tidak cocok dengan iklim tropis kita. Produktivitasnya hanya 1,5–2 ton/ha di Indonesia, jauh di bawah 4–6 ton/ha di negara subtropis (ANTARA News, 24 Juli 2025).
Artinya, jika bicara ketahanan pangan, justru pangan lokal inilah yang paling masuk akal untuk diandalkan.
Memaksakan diri menanam gandum untuk memenuhi kebutuhan nasional sama saja akan mengulang kesalahan sejarah program kedelai. Puluhan tahun mencoba swasembada kedelai tetap gagal; produksinya rendah, dan lebih dari 90 persen kebutuhan masih diimpor. Kini pola serupa hendak diulang untuk gandum.
Nasib program gandum bisa dipastikan mengikuti kegagalan program kedelai. Bukan karena keduanya bukan tanaman tropis, tetapi karena budaya kita tidak konsisten, tidak bisa istiqamah dalam mengembangkan program.
Peluang mengembangkan talas, ubi, singkong, dan aneka kacang lokal yang sudah akrab dengan budaya dan agroklimat yang lebih menjanjikan, mungkin jauh lebih mudah diwujudkan.
Sorgum pernah menjadi makanan pokok di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Singkong menjadi pangan rakyat di Jawa, Lampung, hingga pedalaman Kalimantan. Talas akrab di Bogor, Bali, dan Maluku. Ubi jalar sampai hari ini masih jadi sumber energi utama masyarakat pegunungan Papua. Di Maluku dan Papua, sagu tetap lestari sebagai makanan pokok, dari papeda hingga sinole.
Sejarah telah membuktikan bahwa pangan lokal bukan sekadar alternatif. Tanam lokal bisa menjadi fondasi kehidupan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, bila kita sungguh ingin berdaulat pangan, jalan keluarnya bukan menanam gandum. Buka kembali lumbung sorgum, kebun singkong, ladang talas, rawa sagu, dan petak ubi jalar.
Kedaulatan pangan tropis harus ditegakkan oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan mengandalkan impor yang dikuasai oligarki.